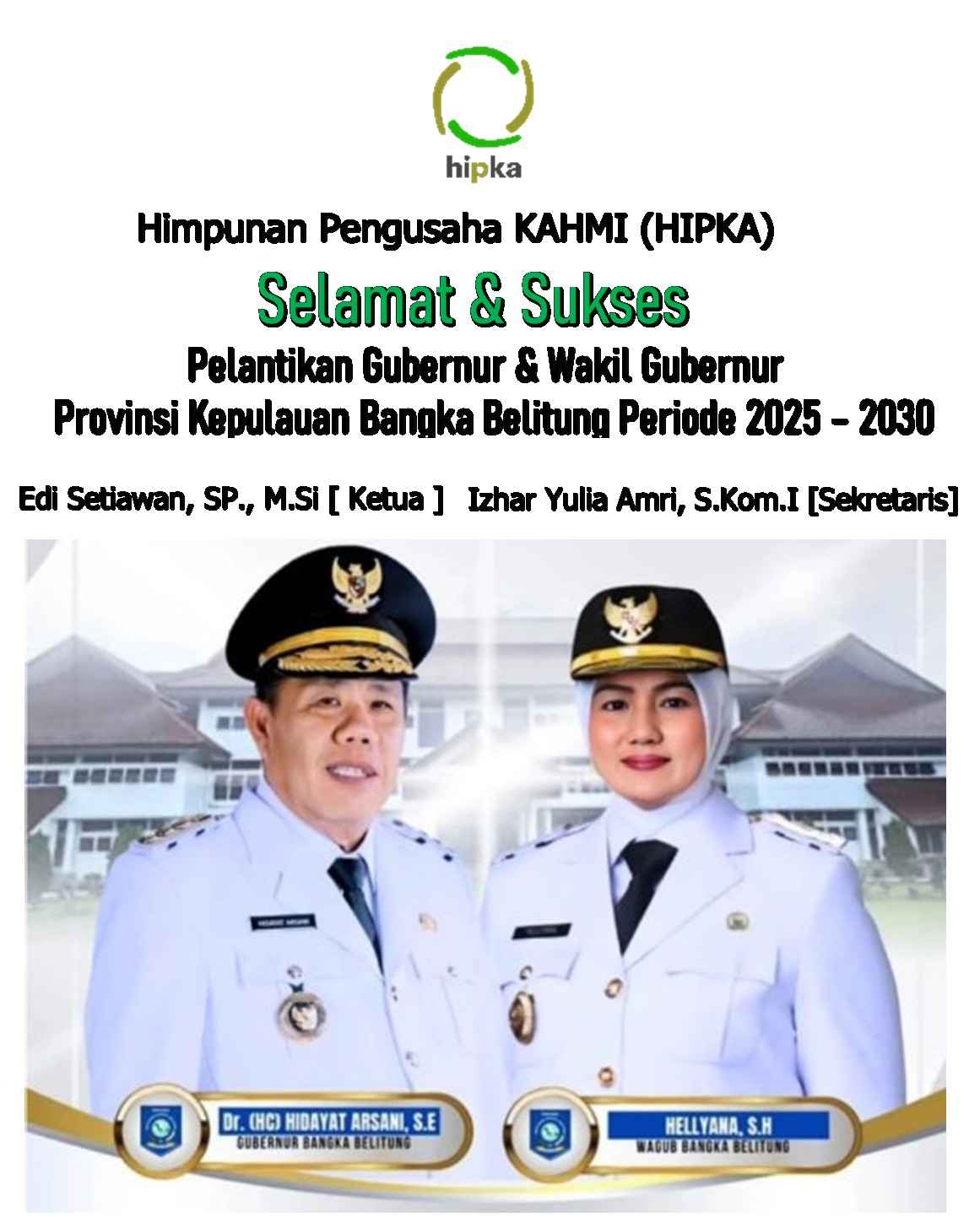Polsek Kelapa Amankan Pawai Taaruf Maulid Nabi Muhammad SAW, Dihadiri Bupati Babar
By beritage |
GETARBABEL.COM, BANGKA BARAT — Polsek Kelapa jajaran Polres Bangka Barat…
Friday, 3 October 2025

Oleh: Maman Supriatman || Alumni HMI
Pengabaian makna literal dalam eskatologi bukanlah tanda kemajuan intelektual, tetapi langkah besar menuju kebutaan. Dajjal lebih suka umat ini menafsirkan dirinya agar menghilang, daripada mempersiapkan diri menghadapi kemunculannya.
Pengabaian terhadap makna literal dalam eskatologi Islam bukan sekadar kecenderungan intelektual modern, melainkan bentuk dekonstruksi narasi profetik yang membutakan umat dari realitas strategis zaman fitnah.
Di tengah dominasi tafsir simbolik yang menjadikan nubuwat sekadar metafora moral, esai ini menelusuri bagaimana warisan pemikiran Sayyid Ahmad Khan, Muhammad Abduh, hingga Fazlur Rahman berperan dalam menjauhkan umat dari geoprofetik, yakni dimensi strategis nubuwat yang membimbing umat menghadapi dinamika global kontemporer.
Dengan menyoroti kecenderungan hermeneutik etis-historis yang mensterilkan teks dari potensi operasionalnya, tulisan ini mengkritisi bagaimana tafsir simbolik justru dapat menjadi alat disinformasi teologis yang melumpuhkan kesiapsiagaan umat.
Dalam konteks inilah, pendekatan Syekh Imran Hosein muncul sebagai koreksi paradigmatik, menggabungkan literalitas nash dengan kontekstualitas geopolitik, untuk mengembalikan Eskatologi Islam sebagai peta jalan strategis, bukan sekadar ruang kontemplatif.
Sayyid Ahmad Khan (1817–1898)
Sebagai pionir modernisme Islam di anak benua India, Sayyid Ahmad Khan menekankan pendekatan rasional terhadap teks-teks agama, termasuk eskatologi.
Dalam “Essays on the Life of Muhammad” (1870), ia menolak eksistensi literal makhluk gaib seperti malaikat dan jin, serta memaknai nubuwat akhir zaman sebagai alegori moral dalam sejarah:
“All descriptions of angels and demons in the Qur’an and Hadith are allegorical references to inner moral states of man.” (hlm. 54)
Dengan logika serupa, figur Dajjal dianggap sebagai simbol kejahilan dan tirani intelektual, bukan entitas nyata.
Rasionalitas dan moralitas ditempatkan sebagai tolok ukur utama, kendati dengan mengorbankan objektivitas teks.
Muhammad Abduh (1849–1905)
Melalui Tafsir al-Manar (bersama Rasyid Rida), Abduh menolak berbagai hadits eskatologis yang ia nilai bertentangan dengan akidah rasional.
Dalam tafsir QS An-Nur: 35, ia menyatakan:
“Tidak ada tempat dalam agama bagi cerita-cerita tahayyul tentang makhluk aneh yang akan datang di akhir zaman. Dajjal bukanlah makhluk bermata satu, tetapi simbol dari fitnah ilmu yang menyesatkan.”
Abduh memandang peradaban Barat modern sebagai “fitnah Dajjal” dalam bentuk sistem, bukan individu.
Pendekatan simbolik ini memang memuat nilai kontekstual, namun menafikan eksistensi personal Dajjal menciptakan kekosongan epistemik dalam kewaspadaan kolektif.
Sistem dapat dipahami dan diantisipasi, tapi figur bisa menyusup dan mengecoh tanpa deteksi.
Fazlur Rahman (1919–1988)
Fazlur Rahman memperluas pendekatan simbolik dalam kerangka hermeneutik moral-historis.
Dalam Islam and Modernity: Transformation of an Intellectual Tradition (1982), ia menegaskan:
“Muslim theology must cease to be a mere repetition of past ideas and instead should reconstruct religious thought so as to become ethically and socially relevant to the present.” (hlm. 147)
Sementara dalam Major Themes of the Qur’an (1980), ia menulis:
“The Qur’an speaks of the End not to satisfy speculative curiosity, but to evoke moral responsibility.” (hlm. 136)
Menurut Rahman, narasi eskatologis bertujuan membangun kesadaran etis, bukan menyampaikan informasi historis-prophetik.
Pandangan ini menjadikan eskatologi sebagai wacana kontemplatif, bukan sebagai peta strategi umat dalam menghadapi realitas global kontemporer.
Kritik terhadap Tafsir Simbolik
Masalah utama dari pendekatan simbolik adalah terputusnya kesinambungan antara nubuwat dan geopolitik.
Dalam era dominasi zionisme, kapitalisme riba, pengawasan digital global, dan hegemoni ideologis Barat, simbolisme semata tidak cukup untuk membaca taktik musuh.
Ketika nubuwat direduksi menjadi metafora moral, umat kehilangan “GPS profetik” yang dirancang untuk menavigasi zaman fitnah.
Sebaliknya, pendekatan Syekh Imran Hosein menawarkan sintesis tekstual-kontekstual: memahami teks secara literal, namun dikontekstualisasikan dalam lanskap geopolitik.
Ia tidak menolak simbolisme, tetapi mengembalikannya ke dalam struktur peristiwa aktual akhir zaman.
Fazlur Rahman memang berjasa membumikan etika Islam di tengah tantangan modernitas. Namun dalam konteks eskatologi, pendekatannya menghasilkan “domestikasi” terhadap nubuwat, menyulapnya menjadi nasihat moral ketimbang kompas strategis.
Padahal, hadits sahih seperti Muslim 5161 yang memaparkan urutan penaklukan Jazirah Arab, Persia, dan Romawi oleh pasukan Imam Mahdi menunjukkan struktur geopolitik prospektif yang faktual.
Tafsir simbolik justru mengaburkan potensi umat dalam membaca dan merespons manuver global Dajjal secara konkret.
Tidak hanya itu, tokoh seperti Nasr Hamid Abu Zayd dan Arkoun menganggap figur eskatologis sebagai “proyeksi ketakutan kolektif”.
Ini adalah disinformation theology, strategi Dajjal untuk mengubah dirinya dari ancaman nyata menjadi mitos.
Solusinya, mengembalikan eskatologi sebagai geoprofetik, menggabungkan kewaspadaan spiritual dengan analisis struktural.
Memahami Dajjal sebagai fakta, bukan simbol, adalah langkah pertama melawannya.
Karena itu, tafsir eskatologis perlu “naik kelas”: dari simbolisme etis yang steril ke strategi geoprofetik yang operasional. Dari etika ke taktik. Dari kontemplasi ke kesiapsiagaan. Dari moralitas pasif ke mobilisasi strategis.
Simbolisasi Figur Eskatologis sebagai Strategi Pengelabuan
Salah satu jebakan intelektual terbesar era modern adalah reduksi figur eskatologis menjadi simbol moral atau metafora peradaban.
Narasi Dajjal, Ya’juj-Ma’juj, Imam Mahdi, dan Nabi Isa sering dikaburkan melalui pendekatan simbolik, padahal hal ini justru membuka celah bagi strategi Dajjal untuk menyamarkan eksistensinya yang konkret.
Dajjal tidak hadir dengan wajah garang, tetapi melalui sistem yang memikat: kapitalisme global, teknologi AI, digitalisasi kontrol, dan relativisme nilai. Ketika umat hanya diajarkan untuk menafsirkan, bukan menghadapi, maka mereka kehilangan daya deteksi terhadap operasi musuh.
Tafsir simbolik yang menolak eksistensi literal figur-figur eskatologis telah melemahkan sensitivitas umat terhadap ancaman riil yang kini beroperasi dalam medan ekonomi, politik, teknologi, dan ideologi.
Syekh Imran Hosein hadir sebagai penyeimbang. Ia tidak meninggalkan simbolisme, namun mengakarnya dalam realitas sejarah. Ia tidak menolak kontekstualisasi, tetapi menjadikannya alat untuk membaca penggenapan janji Tuhan dalam sejarah umat manusia.
Dengan demikian, tafsir eskatologi tidak lagi hanya menjadi ruang moralitas, tetapi medan strategi. Inilah jalan baru menuju kebangkitan geoprofetik Islam.
Epilog: Orkestra Tafsir Para Guru
Di aula sunyi para pemikir,
bergema simfoni tafsir nan lirih,
Ibnu Khaldun memetik dawai sejarah,
Iqbal menyisipkan bait syair pasrah.
Ahmad Khan memoles wahyu jadi etika Barat,
Abduh menenun rasional dalam syariat,
Rasyid Ridha jadi konduktor perubahan,
menarik akal dari rahim wahyu ke peradaban.
Lalu datang sang filsuf bernama Fazlur,
membedah teks seperti dokter bedah,
Arkoun berbisik dalam aksen Paris,
bahwa makna bukan milik langit tapi bahasa. Harun mengalunkan nada kontekstual,
Cak Nur tersenyum: “Islam itu progresif, kawan!”
Namun simfoni ini terus berulang,
diputar oleh tangan-tangan tak tampak, tenang.
Mereka bicara tafsir baru,
tapi nadanya lama dan teratur,
seolah wahyu perlu izin editor,
dan Islam dijahit agar pas di panggung global.
Mereka berdiri gagah di podium sejarah: Ibnu Khaldun dengan sosiologi agungnya, Iqbal dengan puisi pembebasan yang terperangkap dalam estetika, Ahmad Khan dan Abduh yang menjahit wahyu agar serasi dengan busana Eropa, hingga Arkoun yang menaburkan teori dekonstruksi pada halaman mushaf.
Semua tampak revolusioner, namun justru berada dalam jalur yang sangat tertib, bahkan nyaris koreografis: tafsir metaforis dan simbolik.
Mereka semua bermain dalam simfoni yang sama: sebuah narasi besar yang mengklaim pembebasan, tapi justru menjadi alat kontrol yang paling canggih.
Dengan menjadikan teks suci sebagai medan permainan metafora, mereka menciptakan ilusi kebebasan berpikir, sambil diam-diam tunduk pada struktur kekuasaan yang lebih besar: modernitas Barat dengan seluruh epistemologinya.
Fazlur Rahman berbicara tentang historisitas, Muhammad Abduh tentang rasionalisasi, Harun Nasution tentang inklusivisme, tapi semua itu hanya variasi dalam satu partitur yang sudah ditulis oleh proyek Pencerahan.
Mereka mengira sedang membongkar tirani, padahal hanya mengganti borgol dengan rantai yang lebih halus. Kritik mereka terhadap tradisi justru menjadi legitimasi bagi rezim pengetahuan global.
Ironisnya, semakin keras mereka berteriak “pembaruan,” semakin dalam mereka terjebak dalam labirin yang sama: menjadi penyanyi dalam orkestra yang konduktornya tak pernah mereka kenal wajahnya.
Satir ini bukan untuk menafikan kontribusi mereka, tapi untuk mengganggu kepuasan diri kita yang menganggap pembaruan selalu netral dari kuasa.
والله أعلم
MS 16/05/25
(Foto: Ilustrasi/IST)
Posted in SOSBUD
GETARBABEL.COM, BANGKA BARAT — Polsek Kelapa jajaran Polres Bangka Barat…
JAKARTA–Sebanyak 18 pejabat fungsional Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja (PPPK)…
JAKARTA– Tim Jaksa Penyidik pada Direktorat Penyidikan Jaksa Agung Muda…
Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan…
GETARBABEL.COM, BANGKA — Sejumlah ASN…
GETARBABEL.COM, BANGKA — Sungguh miris…
GETARBABEL.COM, BANGKA- Kawasan hutan seluas…