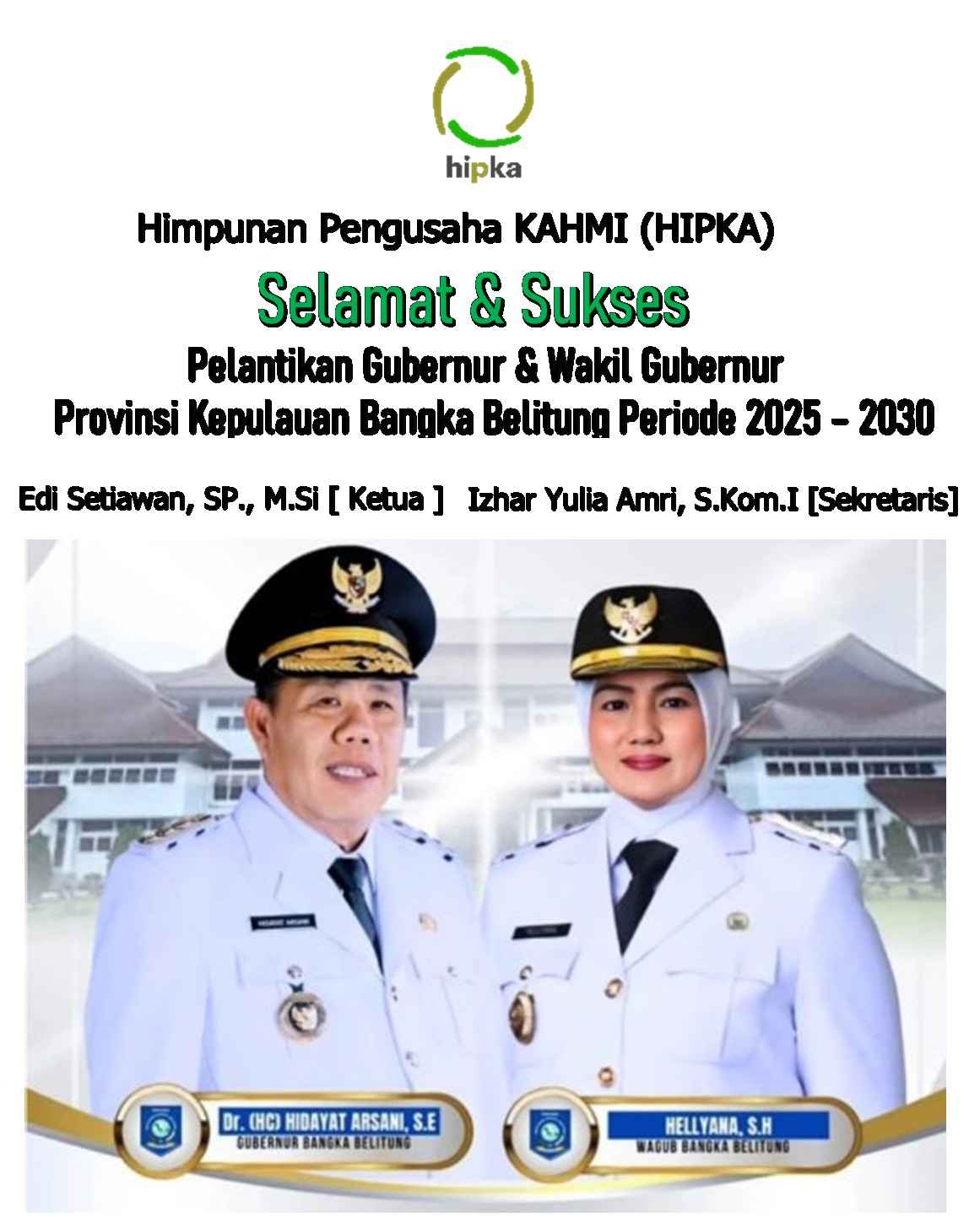Tabrakan Beruntun Libatkan 3 Kendaraan, Mobil Brandweer dan Patwal Hendak Padamkan Kebakaran
By beritage |
GETARBABEL.COM, BANGKA — Kecelakaan lalu lintas (lakalantas) tabrakan beruntun melibat…
Sunday, 14 September 2025

Oleh: Maman Supriatman || Alumni HMI
Esai sebelumnya mengungkap akar krisis peradaban modern: kebutaan bashirah akibat dominasi epistemologi Barat yang sekular-materialistik.¹
Kini, tiba saatnya menerjemahkan kritik epistemologis itu menjadi arsitektur kurikulum operasional.
Reorientasi pendidikan berbasis Epistemologi Islam bukan sekadar wacana teoretis, melainkan proyek peradaban yang memerlukan desain integratif.
Artikel ini merancang kerangka kurikulum berporoskan bashirah (mata hati) sebagai respons terhadap kebutaan spiritual zaman, sekaligus menyiapkan landasan implementasi pedagogis.
Rekomendasi Konferensi Dunia Pendidikan Islam sejak Mekah 1977 menjadi pijakan operasional, terutama penegasan Islamabad (1980) tentang integrasi ilmu naqli-‘aqli dan deklarasi Dhaka (1981) mengenai penanaman nilai tauhid dalam kurikulum.²
Visi Pendidikan: Membangun Insan Berbashirah
Visi pendidikan Islam harus melampaui target materialistik. Artikel ini menawarkan visi: “Membentuk insan berbashirah tajamah (penglihatan hati yang jernih) yang merealisasikan khilāfah fī al-arḍ (pemakmur bumi) melalui integrasi ilmu-ilmu Ilahiyah-insaniyah-kauniyah.”³
Visi ini menyambut seruan Konferensi Mekah (1977) tentang “pendidikan berbasis tauhid” dan rekomendasi Jakarta (1982) untuk “menghubungkan ilmu dengan maqāṣid syarī‘ah.”⁴ Visi ini bertumpu pada dua pilar utama:
Pertama, Tawḥīd al-‘Ulūm (Kesatuan Ilmu). Menghapus dikotomi artifisial antara ilmu agama dan umum sebagaimana ditekankan Konferensi Islamabad (1980): “Ilmu adalah kesatuan organik yang bersumber dari Allah.”⁵
Setiap disiplin ilmu: fisika, ekonomi, sastra, dan lainnya, dikaji dalam kerangka āyātullāh (tanda-tanda Allah).
Fisika misalnya, tidak diajarkan sebagai hukum mekanis semata, melainkan sebagai manifestasi Sunnatullāh (Keteraturan Ilahi) yang mengundang tafakkur (QS 3: 190).
Kedua, Tazkiyat al-Nafs (Penyucian Jiwa). Kurikulum wajib memasukkan modul riyāḍat al-qalb (pelatihan hati) di semua mata pelajaran, selaras resolusi Konferensi Dhaka (1981): “Pendidikan harus membersihkan hati dan mengembangkan akhlak mulia.”⁶
Setiap aktivitas belajar dirancang mengandung dimensi muhāsabah (evaluasi diri), mengingatkan bahwa ilmu tanpa penyucian jiwa bagai “api tanpa cahaya” (Al-Ghazālī).
Struktur Integratif: Pohon Ilmu Berakar Wahyu
Model kurikulum terpadu ini dapat dianalogikan sebagai “Pohon Ilmu” yang organik, mengacu rekomendasi Konferensi Kairo (1987) tentang “struktur kurikulum holistik”:⁷
Pendekatan Integratif dalam Mata Pelajaran
Implementasi kerangka ini membutuhkan dekonstruksi radikal terhadap silabus konvensional, mengaktualisasikan rekomendasi Konferensi Jakarta (1982) untuk “mengislamisasi konten disiplin ilmu”¹¹
Sains Alam mengadopsi pendekatan tafakkur fī khalqillāh (merenungi ciptaan Allah). Aktivitas observasi ekosistem tidak berhenti pada katalogisasi spesies, tetapi diarahkan pada refleksi kemahaciptaan Allah (QS 88: 17-20).
Siswa diajak meneliti simetri daun sambil merenungkan ayat: “Yang menciptakan tujuh langit berlapis-lapis. Tidak akan kau lihat cacat pada ciptaan-Nya.” (QS 67: 3).
Ekonomi dirombak berbasis maqāṣid al-māl (tujuan pengelolaan harta). Simulasi bisnis mengevaluasi dampak sosial-lingkungan berbasis prinsip ḥifẓ al-māl (penjagaan harta) dan keadilan distributif, selaras rekomendasi Konferensi Islamabad: “Ekonomi Islam harus mengutamakan keadilan sosial.”¹²
Peserta didik menganalisis kasus monopolistik melalui lensa hadis: “Tidak halal harta seseorang kecuali dengan kerelaan hatinya.”
Sejarah bertransformasi menjadi eksplorasi ‘ibrah wa ḥikmah (pelajaran dan kebijaksanaan).
Studi kejatuhan peradaban mengidentifikasi kebutaan bashirah kolektif (QS 12: 111), menjawab seruan Konferensi Dhaka: “Sejarah harus menjadi cermin peradaban.”¹³
Sastra dikembangkan sebagai sarana balāghat al-qalb (kefasihan hati). Dekonstruksi puisi Rumi atau Hamzah Fansuri mengeksplorasi simbol-simbol ketuhanan (ishārāt ilāhiyyah), sejalan rekomendasi Kairo (1987) tentang “pemanfaatan warisan sastra Islam.”¹⁴
Evaluasi Holistik: Mengukur Ketaqwaan dan Ketajaman Bashirah
Sistem penilaian konvensional digantikan model tiga dimensi, sesuai rekomendasi Konferensi Cape Town: “Evaluasi pendidikan harus mencakup dimensi spiritual dan sosial.”¹⁵
Instrumen Matrix Tawḥīd dikembangkan untuk memetakan hubungan tema pelajaran (misal: hukum termodinamika) dengan ayat kauniyah dan qur’āniyyah (QS 41: 53), merealisasikan gagasan Konferensi Jakarta tentang “integrasi vertikal ilmu.”¹⁷
Penutup: Menyiapkan Lahan Pedagogis
Kerangka kurikulum ini menuntut revolusi pedagogi yang menumbuhkan bashirah melalui tarbiyat al-qalb (pendidikan hati).
Sebagaimana firman-Nya: “Kami akan perlihatkan tanda-tanda Kami di horison dan dalam diri mereka, sampai jelas bahwa inilah kebenaran.” (QS 41: 53).
Langkah selanjutnya adalah implementasi metodologi transformatif dalam pembelajaran, yang akan dibahas dalam esai berikutnya.
DAFTAR FOOTNOTE
¹ Al-Attas, S.M.N. (1978). Aims and Objectives of Islamic Education, hlm. 19.
² Proceedings of the First World Conference on Muslim Education, Mecca 1977, hlm. 22-25.
³ Wan Daud, W.M.N. (2003). Educational Philosophy of Al-Attas, hlm. 134-137.
⁴ Third World Conference on Muslim Education, Jakarta 1982, Recommendation 4.3.
⁵ Second World Conference on Muslim Education, Islamabad 1980, Resolution 1.1.
⁶ Third World Conference, Dhaka 1981, Declaration Art. 5.
⁷ Fourth World Conference, Cairo 1987, hlm. 87.
⁸ Abdul Hakim Murad (2020). Cognitive Dzikr Model, Cambridge Muslim College.
⁹ Ibn ‘Arabī. Fuṣūṣ al-Ḥikam, Prolog.
¹⁰ Sixth World Conference, Cape Town 1996, hlm. 33.
¹¹ Jakarta 1982, Recommendation 7.2.
¹² Islamabad 1980, Resolution 3.4.
¹³ Dhaka 1981, Declaration Art. 8.
¹⁴ Cairo 1987, hlm. 92.
¹⁵ Cape Town 1996, hlm. 41.
¹⁶ Hashim, R. (2004). Educational Dualism in Malaysia, hlm. 204.
¹⁷ Jakarta 1982, Recommendation 4.1.
والله أعلم
MS 16/06/25
(Foto: ilustrasi/IST)
Posted in IPTEK
GETARBABEL.COM, BANGKA — Kecelakaan lalu lintas (lakalantas) tabrakan beruntun melibat…
GETARBABEL.COM, BANGKA BARAT — Polsek Kelapa jajaran Polres Bangka Barat…
GETARBABEL.COM, BANGKA– Polemik pertambangan timah ilegal di Bangka Belitung semakin…
Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan…
GETARBABEL.COM, BANGKA — Sejumlah ASN…
GETARBABEL.COM, BANGKA — Sungguh miris…
GETARBABEL.COM, BANGKA- Kawasan hutan seluas…